Bahas Bahasa, Ah
- Pambayung

- Apr 9, 2024
- 4 min read
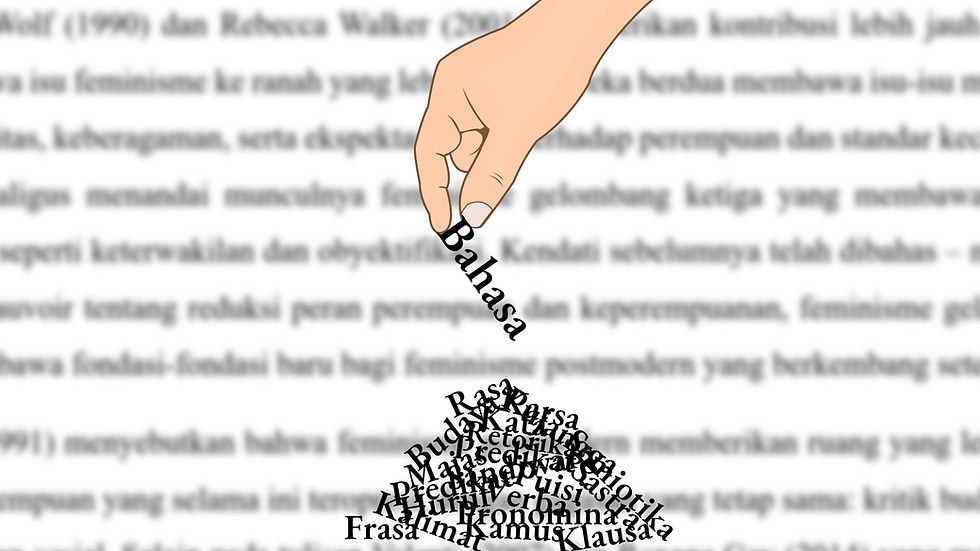
Tempo hari, ketika sedang berbuka di warung tahu telur, saya bertemu kawan lama dari zaman MTs dulu. Setelah berjabat tangan, percakapan kami berlangsung seperti ini:
Dia : "Gimana-gimana?" Saya : "Aman-aman. Kamu sekarang di mana?" Dia : "Aku di ilpol UB."
Dilihat sekilas, percakapan tersebut tidak masuk akal. Pertama-tama, dia hanya mengulang kata tanya "bagaimana" dan saya jawab "aman". Apanya yang bagaimana? Kondisi saya? Kondisi hati ini? Kondisi masyarakat Kediri? Kondisi politik Indonesia? Tapi saya dengan percaya diri menjawab "aman". Padahal kalau pertanyaannya ternyata yang terakhir, tentu tidak aman, hohoho. Pun dengan pertanyaan saya "sekarang di mana". Sudah jelas-jelas dia sedang berada di depan saya. Di warung tahu telur yang sama. Tetapi saya bertanya demikian. Yang lebih absurd, dia justru menjawab dengan tempat dia berkuliah sekarang.
Tapi itulah bahasa.
Ia merupakan seperangkat simbol yang disepakati memiliki artian tertentu dan berfungsi untuk memberikan suatu bentuk pemahaman kepada para penuturnya. Tapi belakangan saya temui fenomena menarik.
Di media sosial, tengah viral sebuah video siniar yang berisikan dua orang figur publik yang membahas mengenai betapa miskinnya kosa kata bahasa Indonesia, sehingga kita tidak bisa menyampaikan maksud dengan detail. Bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang "malas".
Saya memiliki dua pendapat soal hal ini. Pertama mengenai sifat bahasa, dan kedua mengenai fungsi bahasa itu sendiri.
Secara sifat, bahasa tidak bisa disalahkan atas minimnya perbendaharaan kata yang dimilikinya. Menurut saya, ketidakmampuan bahasa untuk menjelaskan sesuatu berasal dari penuturnya sendiri. Untuk kasus di Indonesia, proses pembangunan bahasa kita sudah terinstitusionalisasi di badan bahasa. Pun KBBI juga telah secara berkala memperbarui kosa kata yang termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan lantas apakah bahasa Indonesia tidak dapat mengakomodasi kepentingan untuk menyampaikan maksud dengan baik, atau justru penuturnya yang tidak memiliki kemampuan menyampaikan itu?
Terlepas dari fakta bahwa kedua publik figur dalam siniar tersebut nampak lebih fasih berbahasa Inggris, tidak bisa dimungkiri bahwa masyarakat Indonesia sebagai penutur aktif bahasa Indonesia memang lebih akrab dengan beberapa istilah asing. Dalam keseharian, kita tidak menggunakan kata "galat" melainkan "error" atau "linimasa" alih-alih "timeline". Hal ini karena memang kosa kata baku jarang menjadi arustama dalam percakapan sehari-hari. Poin ini berkaitan dengan argumen saya yang kedua, soal fungsi.
Seperti yang telah saya sebutkan dalam ilustrasi cerita di atas, fungsi bahasa adalah untuk menghubungkan komunikator dan komunikan, memberikan kesepahaman di antara mereka. Selama maksud dapat diutarakan dengan jelas, maka selama itu pulalah bahasa berfungsi. Karenanya, dapat dipahami bahwa kita sering menggunakan kata serapan maupun kata asing untuk berkomunikasi: sesimpel karena kita tidak tahu. Dalam hal ini, menempatkan kesalahan pada bahasa akibat ketidak tahuan kita bukan merupakan hal yang bijak.
Sastrawan telah sejak lama mencoba bereksperimen tentang sejauh mana mereka bisa mendorong batas-batas fungsi bahasa untuk menyampaikan makna. WS Rendra, misalnya, pada tahun 1969 telah menciptakan naskah lakon "bip-bop" dan "Rambate rate rata" yang menggunakan sesedikit mungkin dialog. Naskah yang lantas disebut Goenawan Muhammad sebagai "Teater minikata" ini menunjukkan pada kita esensi bahasa yang lebih jauh daripada menyampaikan makna: menyampaikan rasa.
Pun demikian dengan puisi-puisi kontemporer. Puisi "Malam Lebaran" Sitor Situmorang cuma terdiri atas satu larik. Puisi "Kalian" karya Sutardji Calzoum Bachri bahkan cuma satu kata. Tapi melalui bahasa yang sederhana itu mereka dapat menyampaikan makna. Bahkan rasa.
Akun YouTube Magnify, salah seorang bahasawan, pernah menerangkan bahwa klakson mobil telah menjadi contoh bentuk simbol yang membawa sebenar-benarnya fungsi bahasa dengan cara yang amat sederhana. Hanya dengan satu jenis suara "tin" kita dapat menyampaikan berbagai hal. Klakson sekali untuk meminta orang lain menepi, berkendara lebih cepat, atau mengingatkan bahwa lampu lalu lintas telah berubah hijau. Klakson dua kali untuk menyapa. Klakson panjang ketika marah. Dan seterusnya.
Lantas, apakah bahasa Indonesia telah memenuhi sifat dan fungsi-fungsi tadi? Tentu. Kompleksitas bahasa Indonesia jauh melampaui klakson mobil. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah meletakkan bahasa Indonesia sesuai fungsinya? Atau, justru ketidakmampuan bahasa Indonesia untuk menyampaikan makna adalah ketidakmampuan kita?
Seorang teman turut berkomentar dalam perdebatan di Twitter soal video siniar yang viral itu. Katanya, kalaupun menggunakan kosa kata baku macam renjana, mancakrida, atau siniar, kan tidak semua orang "mengurai lisan selayaknya pujangga masa kerana Sriwijaya". Soal ini, saya setuju. Memang, seperti yang saya uraikan di atas, belum terjadi suatu bentuk pengarusutamaan kosa kata baku dalam bahasa Indonesia. Karenanya, dibutuhkan usaha-usaha pengarusutamaan bahasa Indonesia. Tentu yang paing berperan adalah mereka yang memiliki pengaruh besar, macam industri pertelivisian atau periklanan. Namun apabila bukan kita yang melestarikan bahasa sendiri, lantas siapa? Jadi mari berbangga menggunakan bahasa Indonesia. Mulai dari kita.
Ibu Tanti, guru bahasa Indonesia saya dulu menyebutkan bahwa kata yang ada dalam bahasa dapat mengalami pergeseran makna. Maka, bukan mustahil apabila lima atau sepuluh tahun kedepan kita dapat menemukan kata-kata baku dalam bahasa Indonesia menggantikan istilah-istilah asing yang kerap kita gunakan. Kendati tipis kemungkinannya, memiliki harapan tidak ada salahnya, kan?
Karenanya, biarkan saya menutup tulisan ini dengan berefleksi kepada fungsi bahasa itu sendiri: memberikan pemahaman. Kita harus paham bahwa bahasa tercipta agar kita saling mengerti, alih-alih memusihi. Karenanya, perdebatan mengenai mana bahasa yang seolah-olah superior dan inferior dibanding bahasa lainnya justru menjadi usaha yang kontraproduktif terhadap fungsi bahasa itu sendiri. Kita harus paham bahwa bahasa berasal dari konstruk sosial dan kultural masyarakat. Latar belakang masyarakat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan pascakolonial memudahkan lahirnya asimilasi budaya, sehingga memberikan khazanah perbendaharaan kata serapan yang luar biasa. Kita harus paham bahwa setiap bahasa memiliki fitur masing-masing, yang berasal dari kebutuhan masyarakatnya untuk berkomunikasi. Bahasa Inggris yang memiliki heteronormativitas atau Prancis yang memiliki nomina feminin dan maskulin, atau bahasa Cherokee, yang memiliki fitur evidensialitas.
Maka, mari saling memahami. Bukan sekadar memahami makna, kita juga harus mulai belajar memahami rasa. Sebab bukankah itu sejatinya fungsi bahasa?







Comments